Kajian Kitab Umdatul Ahkam – 39, Dr. Emha Hasan Ayatullah, M.A
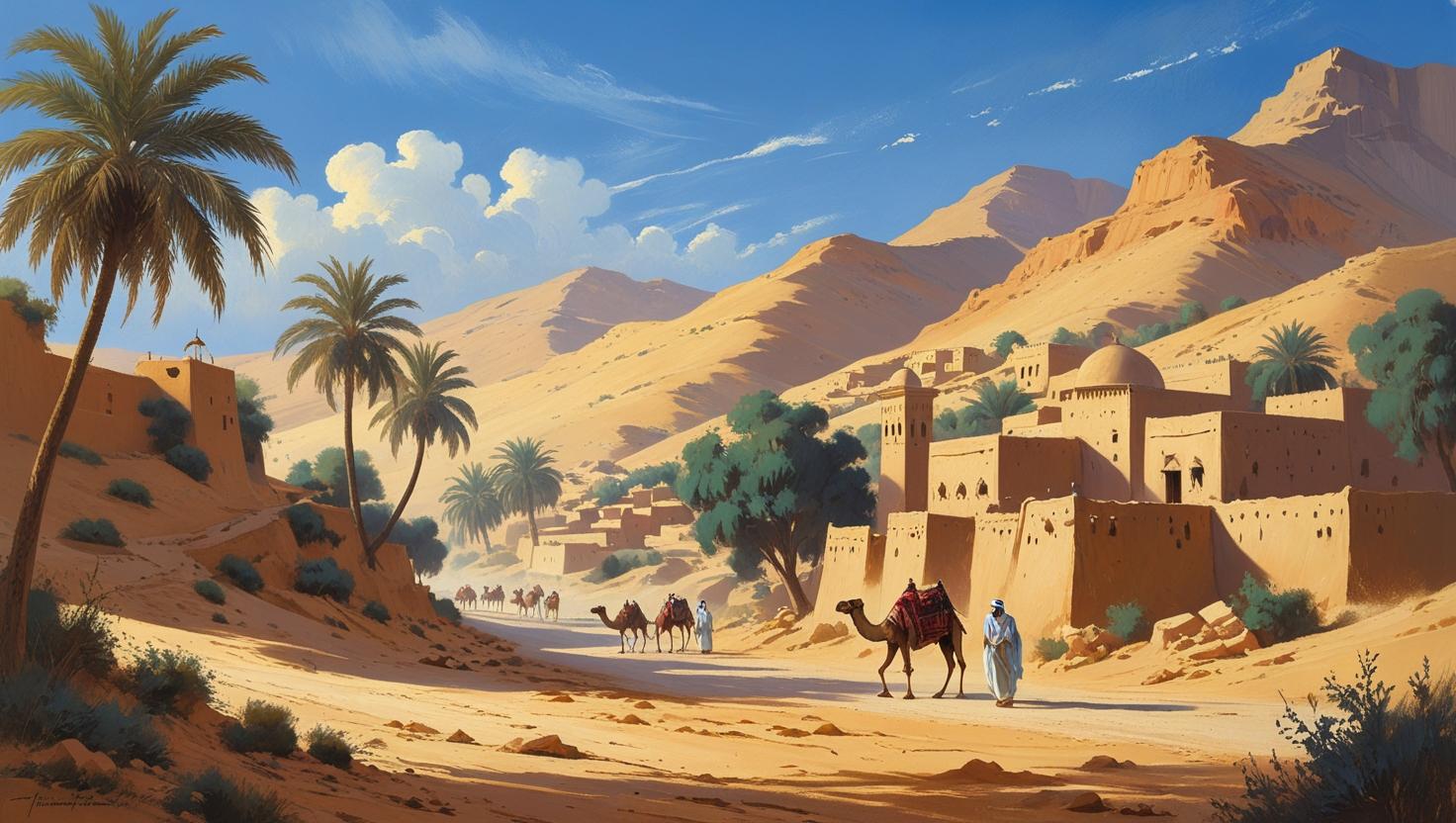
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.
Kita patut berbangga dan berbahagia serta bersyukur kepada Allah ketika kita dipilihkan untuk berada dalam lingkungan (بِيْئَةٍ صَالِحَةٍ) yang baik, di mana kita dapat beribadah kepada Allah sambil belajar. Belajar ilmu syar’i adalah sesuatu yang mahal. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an:
إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا
“Wahai Muhammad, Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.”
Jika kita merenungi bahwa ilmu ini berat, maka itu memang benar adanya, bahkan sangat berat. Para ulama, di antaranya Syekh al-Albani rahimahullah, menyatakan bahwa sunnah itu susah dan berat. Maka, jangan sampai beratnya sunnah tersebut kita tambahi dengan beratnya perangai kita. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa seseorang yang belajar sangat membutuhkan taufik dari Allah. Tidak semua orang cerdas akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Jika hanya sekadar ijazah, hal itu sangat mudah didapatkan di zaman sekarang. Bahkan, kita sering mendengar istilah “pembodohan terstruktur” yang terjadi di banyak institusi pendidikan. Sejak kecil, yang terpenting adalah siswa diluluskan agar sekolahnya tidak kehilangan akreditasi. Pola ini berlanjut dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jika ada siswa yang gagal, yang disalahkan adalah gurunya. Di perguruan tinggi, ada mahasiswa yang nilainya bukan hanya dikatrol, tetapi seolah “ditendang” agar lekas lulus. Doa kelulusannya mungkin tulus, tetapi bisa jadi maksudnya adalah agar kita bisa “beristirahat” dari mahasiswa tersebut. Intinya, jika hanya sekadar ijazah, itu sangat mudah diperoleh, tetapi ilmu sejati itu mahal.
Ilmu itu sangat mahal. Kita pernah mendengar kisah Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ahli hadis yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Beliau adalah seorang pendekar, jutawan dermawan, mujahid, alim, fakih, dan juga seorang yang zuhud. Dalam biografinya dinukilkan bahwa beliau setiap hari membaca hadis. Suatu ketika, saat beliau keluar sebentar, seseorang bertanya, “أَلَا تَسْتَوْحِشُ أَنْتُمْ؟” (Apakah engkau tidak merasa bosan terus-menerus membaca hadis?). Beliau menjawab, “كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟” (Bagaimana aku akan bosan, sementara aku senantiasa bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam?). Ketika ditanya mengapa beliau terus-menerus membaca dan menulis hadis, beliau berkata, “لَعَلَّ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ أَنْتَفِعُ بِهَا لَمْ أَكْتُبْهَا بَعْدُ” (Bisa jadi kalimat yang akan bermanfaat untukku kelak belum aku dapatkan dan belum aku tulis). Ini menunjukkan bahwa belajar membutuhkan waktu yang panjang, keikhlasan yang besar, dan kesungguhan yang luar biasa.
Maka, wajar jika para ulama ketika membahas karakter seorang penuntut ilmu (طَالِبُ الْعِلْمِ), mereka mengupasnya dari semua aspek, terutama aspek ibadah. Proses belajar tidak hanya sekadar masuk di tahun pertama, kemudian lulus di tahun terakhir dengan gelar sarjana. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kualitas ibadah seseorang kepada Allah. Mungkin seseorang bersemangat di awal, tetapi setelah hafalannya banyak, ia justru menjadi malas. Banyak orang yang seperti itu, dan kita melihat ini sebagai sebuah sisi kemunduran dan kegagalan.
Dahulu, sebelum seseorang menjadi pembawa ilmu, ia dipersiapkan dengan matang. Imam Malik rahimahullah pernah bercerita tentang persiapan yang diberikan oleh ibunya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab at-Tamhid. Imam Malik berkata, “Ketika aku masih kecil, ibuku menyiapkan pakaian untukku, lalu memakaikanku imamah.” Anak kecil sebenarnya tidak ada masalah jika tidak memakai imamah. Meskipun sebagian Ahlul Hadis menyatakan bahwa keluar rumah dengan kepala terbuka adalah sebuah aib dan termasuk perusak wibawa (خَوَارِمُ الْمُرُوْءَةِ), begitulah kesempurnaan yang mereka jaga. Lihatlah bagaimana para ulama dahulu, bahkan orang tua mereka pun mengerti adab dan sopan santun. Anak kecil yang akan hadir di majelis ilmu pun dipakaikan imamah. Ibunya berkata:
يَا بُنَيَّ، اذْهَبْ إِلَى مَجْلِسِ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَتَعَلَّمْ مِنْ سَمْتِهِ وَأَدَبِهِ قَبْلَ حَدِيْثِهِ وَفِقْهِهِ
“Wahai anakku, pergilah ke majelis Rabi’ah (gurunya), lalu pelajarilah akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikihnya.”
Pesan seperti ini sudah ditanamkan sejak kecil. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa seorang penuntut ilmu wajib memiliki سَكِيْنَةً وَوَقَارًا (ketenangan dan kewibawaan). Ini adalah wasiat dari para ulama. Seorang penuntut ilmu harus berbeda dari orang lain; ia harus tenang dan teduh, tidak seperti orang awam yang tidak pernah belajar, apalagi jika yang dipelajari adalah ilmu agama. Tidak pantas ia terlihat seperti orang-orang yang tidak belajar.
Imam Syafi’i juga menyebutkan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya disiplin. Kita memang harus berupaya beradaptasi dengan zaman. Orang sekarang menyebutnya “gaya belajar milenial,” yang menggunakan perangkat elektronik dan berbagai sarana (وَسِيْلَة). Hal ini tidak menjadi masalah selama hukumnya mubah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi karakter penuntut ilmu sejak zaman dahulu yang mereka pelajari, yaitu sifat yang mahal di zaman ini: تَعْظِيْمُ النُّصُوْصِ (mengagungkan nas-nas Al-Qur’an maupun hadis). Mereka sangat mengagungkannya. Di zaman sekarang, barangkali seseorang disebut “pakar” saja sudah merasa bangga seperti Syaikhul Islam, padahal ia hanya menulis beberapa tulisan dan belum tentu hafal.
Ilmu ini mahal, dan tujuan utama kita belajar adalah untuk mencari rida Allah. Belajar bukan sekadar bersaing untuk menghadapi tahun 2030 atau 2050. Manusia akan menua, mati, dan generasi akan berganti, tetapi yang terpenting adalah apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak. Jika kita menjadi baik, maka yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri.
Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu pernah menyatakan:
“Hendaklah seorang penghafal Al-Qur’an (حَامِلُ الْقُرْآنِ)…”
Penghafal Al-Qur’an di sini tidak hanya berarti orang yang menghafal, meskipun sebagian ulama menafsirkannya demikian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa Ahlul Qur’an adalah orang yang mempelajari isi Al-Qur’an dan mengamalkannya. Tidak pantas seorang Qari’ul Qur’an (pembaca Al-Qur’an) berlaku seperti orang awam. Ketika orang lain tertidur di malam hari, mestinya ia salat. Ketika orang lain tidak berpuasa, ia berpuasa. Bahkan, ketika orang lain tertawa terbahak-bahak dan merasa bahagia, pantas baginya untuk bersedih, terlihat murung, dan memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang sedang galau biasanya banyak berpikir, “Besok ujian, saya harus paham, saya punya banyak tanggung jawab.” Sementara itu, orang yang tidak punya beban akan tertawa-tawa saja, seolah jauh dari ujian atau baru saja selesai ujian. Kebahagiaan mahasiswa yang paling luar biasa biasanya terjadi dalam dua fase: saat pertama kali masuk kuliah dan saat akan meninggalkan kampus setelah lulus memakai toga, seolah-olah sudah berhasil masuk surga, terutama setelah berkali-kali remedi.
Hendaklah sikap seorang penuntut ilmu berbeda. Ketika orang lain hanya memikirkan dunia, kita memikirkan akhirat. Kita menghafal dalam rangka ibadah, membaca dalam rangka ibadah, dan bukan hanya untuk ujian, tetapi untuk bekal sampai ke akhirat. Karakter seperti ini akan terbentuk dan terbawa ketika ia menyampaikan ilmu. Oleh karena itu, para ulama ketika akan belajar kepada seorang guru, yang mereka lihat bukanlah titelnya, melainkan bagaimana ibadahnya. Ibrahim an-Nakha’i rahimahullah mengatakan bahwa mereka akan melihat terlebih dahulu bagaimana salat dan akhlak seorang guru, baru kemudian mereka belajar kepadanya. Sebagaimana pernah kami sampaikan, Syu’bah bin al-Hajjaj pernah hampir belajar hadis kepada seorang guru, tetapi kemudian tidak jadi karena melihat salatnya jelek. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat memperhatikan dan menilai dari sisi lahiriah, karena sisi batin tidak ada yang mengetahui.
Mahasiswa yang bisa disiplin dan istikamah dari awal hingga lulus, berusaha menjaga salatnya, dan mencari lingkungan yang mendukung agar tetap istikamah, ini adalah sesuatu yang mahal. Terkadang, saya merasa sedikit gemas ketika di tengah-tengah pelajaran ada mahasiswa yang keluar kelas dengan alasan hendak salat. Padahal, kita menunggu azan selesai agar tidak berbicara saat azan, dan setelah itu pelajaran dilanjutkan, baru kemudian salat. Mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan untuk keluar mencari tempat salat tercepat, bukan yang paling khusyuk. Ini dilakukan agar setelah kuliah selesai, ia bisa langsung istirahat. Kita belajar bukan hanya untuk menyelesaikan studi, tetapi bagaimana kita melaksanakannya dengan baik. Inilah yang seharusnya menjadi “bandrol” mahal kita.
Jika orang di luar sana mengetahui ada مَرْكَزُ السُّنَّةِ (pusat sunnah) atau tempat yang menerapkan sunnah, mereka akan mencarinya dari jauh. Namun, kita yang sudah berada di tempat seperti ini justru terkadang mencari yang paling cepat di luar. Apakah boleh memberikan nama مَرْكَزُ السُّنَّةِ pada suatu tempat? Tentu saja boleh, ini seperti sebuah rekomendasi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ‘anhu pernah menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, sebuah kisah yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Ketika Umar bin Khattab berada di Makkah, sampai kabar kepadanya bahwa ada seseorang yang berkata, “Nanti kalau Umar bin Khattab wafat, aku akan memilih si Fulan sebagai khalifah. Dulu Abu Bakar juga dipilih dengan mudah oleh beberapa orang yang datang ke Saqifah Bani Sa’idah, dan alhamdulillah aman sampai sekarang.” Mendengar hal ini, Umar sangat marah dan berkata, “Nanti setelah zuhur, aku akan berkhotbah untuk memperingatkan orang-orang dari perkataan semacam ini.”
Namun, Abdurrahman bin Auf menasihatinya, “Wahai Amirul Mukminin, jangan sekarang. Saat musim haji, yang banyak datang ke majelis ini adalah orang-orang awam (جُهَّال). Nanti jika engkau berkhotbah, banyak orang akan salah memahami perkataanmu dan menyebarluaskannya tidak pada tempatnya. Tunggulah sampai kita kembali ke Madinah. Di sana adalah tempat sunnah dan tempat hijrah para sahabat. Di sana banyak para penuntut ilmu (طُلَّابُ الْعِلْمِ). Sampaikanlah di sana.” Akhirnya, Umar bin Khattab menyampaikan khotbah tersebut di Madinah.
Maka, sebenarnya menamakan suatu tempat sebagai “tempat sunnah” itu baik dan tidak ada masalah, asalkan tidak disertai dengan تَزْكِيَة (merekomendasikan diri sendiri) dengan mengatakan, “Ini tempat sunnah, selainnya adalah bid’ah.” Ini adalah sikap yang salah.
Pembahasan Hadis: Sunnah Bertakbir dalam Shalat
Kita akan melanjutkan pembahasan dua hadis. Tiga bulan yang lalu, sebelum liburan, kita sampai pada pembahasan tata cara sujud, yaitu hadis ke-92, kemudian kita melompat ke hadis ke-99 atau ke-97 karena pembahasannya sama tentang sujud, lalu ke hadis 102. Sekarang, kita kembali ke hadis ke-93 dan 94 tentang syariat bertakbir pada setiap perpindahan rukun.
Jumhur ulama menyatakan bahwa semua takbir yang kita ucapkan (اللهُ أَكْبَرُ) hukumnya sunnah, kecuali Takbiratul Ihram yang hukumnya wajib. Bahkan, banyak ulama yang menganggap Takbiratul Ihram sebagai rukun salat. Adapun takbir-takbir lainnya, seperti takbirul intiqal (takbir perpindahan) dari rukuk ke sujud, dari sujud ke duduk, dan seterusnya, hukumnya sunnah menurut jumhur.
Namun, mazhab Hanabilah (Hanbali) berpendapat bahwa takbir-takbir tersebut hukumnya wajib. Sehingga, jika seseorang meninggalkannya karena lupa, ia harus melakukan sujud sahwi. Sekalipun hukumnya sunnah, tidak pantas bagi seseorang untuk diam saja saat perpindahan rukun, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selalu bertakbir. Ini berarti sunnah dalam salat adalah mengucapkan lafaz takbir tersebut dengan lisan, bukan hanya di dalam batin atau dibayangkan. Sebagian murid Syekh al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa di antara kesalahan orang dalam salat adalah tidak bertakbir ketika menjadi makmum dengan alasan semua sudah ditanggung oleh imam. Akibatnya, banyak makmum yang lupa sudah berapa rakaat salatnya karena tidak ada yang menegur imam ketika keliru. Ini adalah kesalahan. Sunnahnya, seorang makmum tetap mengucapkan takbir (اللهُ أَكْبَرُ) meskipun tidak dengan suara keras. Ini adalah pendapat yang kuat, wallahu a’lam.
Hadis Pertama: Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ…
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika berdiri (حِيْنَ يَقُوْمُ). Kata حِيْنَ (ketika) menunjukkan bahwa takbir diucapkan bersamaan dengan dimulainya gerakan. Imam an-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa takbir dimulai bersamaan dengan gerakan dan berakhir bersamaan dengan selesainya gerakan. Gerakan-gerakan salat pada umumnya pendek, sehingga ini tidak menjadi masalah. Yang mungkin menjadi perhatian adalah gerakan yang panjang, seperti bangkit dari sujud menuju berdiri. Berdasarkan keumuman riwayat ini, takbir diucapkan sepanjang gerakan tersebut.
Lafaz “يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ” (bertakbir ketika berdiri) menunjukkan kewajiban berdiri bagi yang mampu, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Berdiri dalam salat fardu adalah rukun. Jika tidak mampu, boleh duduk. Jika tidak bisa juga, boleh berbaring. Jika tidak mampu lagi, cukup dengan isyarat mata. Jika itu pun tidak bisa, maka ia disalatkan. Adapun untuk salat sunnah, seseorang boleh memilih untuk duduk, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terkadang salat sambil duduk, bahkan menggabungkan antara berdiri dan duduk. Ada riwayat beliau pernah salat malam, mengawalinya dengan berdiri, lalu ketika bacaannya akan dipanjangkan, beliau duduk. Setelah bacaannya panjang, ketika akan rukuk, beliau berdiri kembali (قَامَ فَرَكَعَ), baru kemudian rukuk. Menggabungkan berdiri dan duduk dalam salat sunnah tidak masalah, hanya saja pahalanya setengah dari yang berdiri, kecuali jika ia sakit. Jika sakit, pahala salat duduknya sempurna.
Kemudian hadis melanjutkan: “ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ” (kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk rukuk). Lafaz takbir ini juga diikuti oleh makmum. Sebagian ulama berpendapat takbir hanya untuk imam dengan tujuan mengingatkan makmum. Namun, al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan ini hanya pendapat, sementara apa yang telah ditegaskan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi sunnah bagi semua. Mayoritas salat Nabi adalah sebagai imam, dan beliau hampir tidak pernah menjadi makmum kecuali dalam beberapa kesempatan.
Hadis berlanjut: “ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ” (kemudian beliau mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk). Ucapan ini dikenal dengan tasmi’. Ini diucapkan oleh imam dan orang yang salat sendiri (munfarid).
Bagaimana dengan makmum? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan makmum juga mengucapkannya berdasarkan keumuman contoh dari Nabi. Sebagian lain mengatakan tidak, berdasarkan hadis lain: “Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika imam mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, maka ucapkanlah رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.” Ini menunjukkan adanya pembagian tugas: imam melakukan tasmi’, makmum melakukan tahmid (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). Mazhab Hanafiah berpendapat demikian. Namun, pendapat lain menyatakan imam mengucapkan keduanya, sementara makmum hanya mengucapkan tahmid. Ada pula yang berpendapat keduanya (imam dan makmum) mengucapkan secara lengkap. Wallahu a’lam, jika makmum hanya mengucapkan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, salatnya tetap sah.
Selanjutnya: “ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا” (Kemudian beliau mengucapkan ketika berdiri tegak: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk sujud). Beliau terus melakukan hal ini di setiap perpindahan rukun hingga salatnya selesai. Ini menunjukkan bahwa bertakbir adalah sunnah dalam salat.
Beliau juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua (setelah tasyahud awal) menuju rakaat ketiga. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, disebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya pada empat posisi: Takbiratul Ihram, ketika akan rukuk, ketika bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Adapun ketika sujud, jumhur ulama berpendapat tidak mengangkat tangan, meskipun Syekh al-Albani menukil riwayat yang mensahihkan adanya mengangkat tangan saat akan sujud.
Imam Malik rahimahullah memiliki pendapat berbeda mengenai waktu takbir. Dalam satu riwayat, beliau menyatakan takbir diucapkan setelah berdiri tegak. Beliau menukil dalam kitab al-Muwaththa’ bahwa sebagian sahabat dan ulama salaf dulu bertakbir hanya ketika sudah berdiri. Namun, murid Imam Malik, Abdullah bin Wahab, menjelaskan bahwa bertakbir setelah berdiri itu lebih afdal, tetapi memulainya dari bawah juga diperbolehkan. Khilaf seperti ini adalah hal biasa. Yang salah adalah jika kita tidak bertakbir sama sekali dan hanya diam. Zikir adalah amalan lisan, bukan hanya hati.
Hadis Kedua: Hadis Mutharrif bin Abdillah
قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ…
Mutharrif bin Abdillah, seorang Tabi’in, berkata, “Aku pernah salat bersama ‘Imran bin Hushain (seorang sahabat Nabi) di belakang Ali bin Abi Thalib.” Saat itu Ali menjadi imam karena beliau adalah khalifah. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa salat ini terjadi setelah Perang Jamal, yang menunjukkan bahwa dalam kondisi perang pun mereka tetap salat. Dulu, merupakan kebiasaan bahwa pejabat negara sekaligus menjadi imam dan khatib.
Mutharrif menceritakan: “فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ” (Ali jika sujud beliau bertakbir, jika mengangkat kepalanya (dari sujud) beliau bertakbir, dan jika bangkit dari dua rakaat (tasyahud awal) beliau bertakbir). Setelah salat selesai, ‘Imran bin Hushain memegang tangan Mutharrif dan berkata, “لَقَدْ ذَكَّرَنِيْ هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” (Orang ini (Ali) telah mengingatkanku pada cara salat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam).
Perkataan ini, menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, mengisyaratkan bahwa kebiasaan bertakbir pada setiap perpindahan rukun ini sudah lama ditinggalkan oleh sebagian orang pada masa itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Musa al-Asy’ari juga berkata, “ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِمَّا نَسِيْنَاهَا وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمْدًا” (Ali telah mengingatkan kita pada salat yang dulu kita lakukan bersama Rasulullah, yang mungkin telah kita lupakan atau sengaja kita tinggalkan).
Ketika ditanya siapa yang pertama kali meninggalkan takbir ini, dalam riwayat Musnad Ahmad disebutkan, “أَوَّلُ مَنْ تَرَكَهُ عُثْمَانُ” (Yang pertama meninggalkannya adalah Utsman), ketika suara beliau mulai melemah, mungkin karena kondisi politik saat itu atau karena beliau sudah mulai sakit. Riwayat lain dari ath-Thabarani menyebutkan Mu’awiyah, dan riwayat Abu ‘Ubaid menyebutkan Ziyad (bawahan Mu’awiyah). Ath-Thahawi juga menyebutkan bahwa dulu sebagian kalangan dari dinasti Bani Umayyah tidak bertakbir ketika turun (sujud), tetapi masih bertakbir ketika berdiri (rukuk dan Takbiratul Ihram). Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan penguasa dapat berpengaruh pada masyarakat.
Inilah mengapa kita berharap para pejabat kita minimal melaksanakan salat, agar menjadi contoh bagi masyarakat. Semoga Allah menjadikan kita istikamah di atas sunnah.
Tanya Jawab
Pertanyaan: Bagaimana jika kita lupa takbiratul intiqal dan baru ingat ketika sampai pada rukun berikutnya?
Jawaban: Menurut pendapat jumhur ulama yang menyatakan takbir ini sunnah, maka tidak ada masalah dan salat tetap sah. Namun, menurut mazhab Hanabilah yang mewajibkannya, maka ia harus melakukan sujud sahwi jika meninggalkannya karena lupa.
Pertanyaan: Bagaimana penjelasan hadis larangan turun sujud seperti unta, dan apakah mendahulukan tangan lebih afdal?
Jawaban: Ini adalah masalah khilaf di kalangan ulama. Terdapat dua hadis yang menjadi dasar, dan keduanya memiliki catatan pada sanadnya. Hadis dari Wa’il bin Hujur menyebutkan Nabi meletakkan lututnya sebelum tangannya. Namun, riwayat ini memiliki perawi yang bermasalah pada hafalannya. Hadis dari Abu Hurairah melarang turun seperti unta dan memerintahkan meletakkan tangan sebelum lutut, namun riwayat ini juga memiliki perawi yang dipermasalahkan. Karena kedua hadis sama-sama memiliki catatan, maka kedua cara (mendahulukan lutut atau tangan) diperbolehkan untuk diamalkan.
Pertanyaan: Apakah berzikir menggunakan tasbih tidak disyariatkan, mengingat Ibnu Mas’ud pernah mengingkarinya?
Jawaban: Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa jari-jemari kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban (مَسْؤُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ). Maka, lebih utama menggunakan jari-jemari kita untuk berzikir.
Pertanyaan: Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) itu adalah sunnah?
Jawaban: Ada beberapa riwayat yang mengarah pada makna ini. Contohnya adalah sikap Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu. Beliau meyakini salat musafir adalah dua rakaat, tetapi ketika Amirul Haj saat itu, Utsman bin Affan, salat empat rakaat (karena khawatir orang awam salah paham), Ibnu Mas’ud pun ikut salat empat rakaat. Ketika ditanya, beliau menjawab, “الْخِلَافُ شَرٌّ” (Perbedaan pendapat itu buruk). Cara terbaik keluar dari perbedaan pendapat adalah dengan mengikuti dalil yang paling kuat.
Pertanyaan: Bagaimana hukum menambahkan ‘alaihissalam atau karramallahu wajhah setelah nama Ali?
Jawaban: Mengucapkan selawat dan salam kepada para sahabat secara umum diperbolehkan. Nabi pernah bersabda, “اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى” (Ya Allah, berikanlah selawat kepada keluarga Abu Aufa). Yang menjadi masalah adalah mengkhususkannya untuk sahabat tertentu dan tidak untuk yang lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penambahan lafaz-lafaz seperti itu di beberapa kitab sering kali bukan tulisan asli dari ulamanya, melainkan tambahan dari para penyalin naskah (مِنْ عَمَلِ النُّسَّاخِ).
Pertanyaan: Apakah imam wajib melihat tafsir ayat yang akan dibaca agar tidak keliru saat berhenti (waqaf) dan memulai (ibtida’)?
Jawaban: Tidak harus membaca tafsir. Aturan utamanya adalah berhenti di tempat yang tidak merusak makna. Jika harus membaca tafsir setiap akan salat, tentu akan memakan waktu yang sangat lama.
Pertanyaan: Bolehkah memakai minyak wangi yang kita suka, namun sebagian orang kurang suka baunya?
Jawaban: Ini masalah selera. Jika kita tahu ada orang yang tidak suka, sebaiknya kita menjauh darinya. Diharapkan juga agar tidak memakai minyak wangi secara berlebihan hingga mengganggu orang di sekitar.
Pertanyaan: Apa hukum bersedekap setelah bangkit dari rukuk (i’tidal)?
Jawaban: Ini juga masalah khilaf di kalangan ulama. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa seseorang boleh memilih untuk bersedekap kembali atau membiarkan tangannya lurus. Alasannya, i’tidal masih terhitung sebagai posisi berdiri dalam salat, dan dalam posisi berdiri, tangan diletakkan di atas dada. Sementara ulama lain, seperti Syekh al-Albani rahimahullah, menganggapnya bid’ah karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Masing-masing pendapat ini dianut oleh ulama, dan tidak masalah jika seseorang ingin mengamalkannya.
Pertanyaan: Jika makmum masbuk pada rakaat kedua atau ketiga, apakah ketika ia berdiri untuk menyempurnakan kekurangan rakaatnya ia harus bertakbir dan mengangkat tangan?
Jawaban: Jika ia ingin bertakbir, itu baik. Jika tidak pun tidak masalah, karena semua itu termasuk sunnah. Wallahu a’lam.
Pertanyaan: Apa kadar lelah yang membolehkan seseorang salat duduk atau menjamak salat?
Jawaban: Tergantung pada tingkat kelelahannya. Jika lelahnya sangat parah hingga gemetar dan tidak kuat berdiri, atau jika ia baru pulang dari perjalanan jauh dan khawatir jika tidur akan terlewat waktu salat berikutnya, maka ia boleh menjamak salat. Namun, jika ia masih kuat untuk mengobrol atau melakukan aktivitas lain, maka tidak selayaknya ia menjamak. Begitu pula dengan salat sambil duduk. Jangan karena sedikit lelah langsung memilih duduk. Jangan sampai kita menganggap urusan salat lebih remeh daripada urusan dunia.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.
وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



