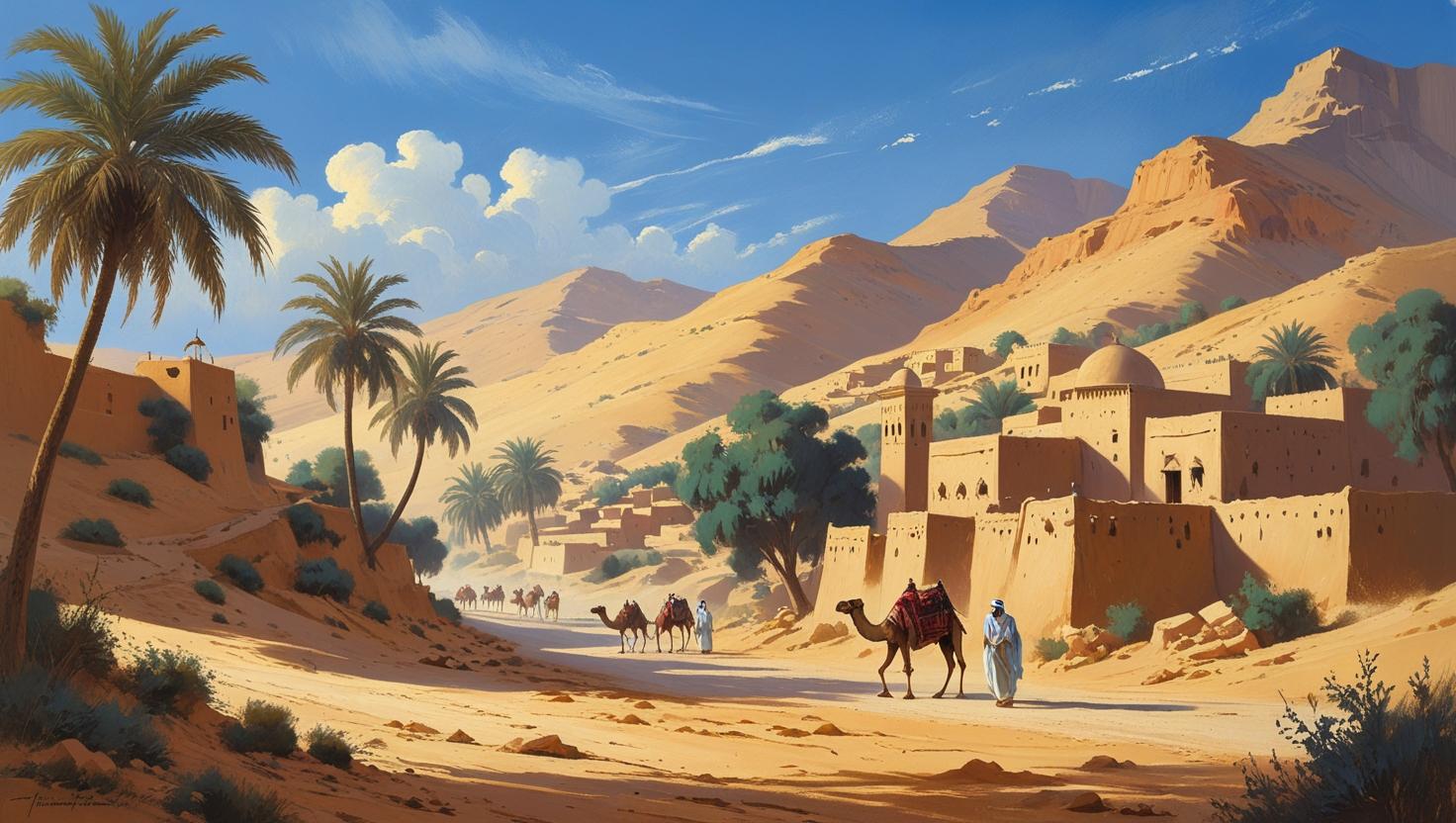Kajian Kitab Lum’atul I’tiqad #11

Berikut adalah transkripsi dan penyuntingan dari kajian yang Anda berikan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.
Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul ‘alamin yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya; kenikmatan kesehatan, waktu luang, dan tentunya nikmat hidayah yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta’ala limpahkan kepada nabi kita Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman.
Para hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, kita masih bersama kitab Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Masih pada pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas sifat Al-Ghadab (sifat marah bagi Allah), kemudian sifat Al-Kurh (Allah Subhanahu wa Ta’ala membenci), kemudian juga sifat turun (An-Nuzul), kemudian sifat Ta’ajjub (heran atau kagum), kemudian yang terakhir adalah sifat Adh-Dhahik (tertawa). Telah disebutkan oleh mualif rahimahullah dalil-dalilnya dan penjelasan secara singkat bahwa kewajiban kita adalah menetapkan sifat-sifat tersebut karena memang telah datang dalil yang shahih yang menunjukkan tentangnya. Kita yakini bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk, turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk, tertawanya Allah berbeda dengan tertawanya makhluk, sehingga kita pun terbebas dari penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhluk-Nya.
Kaidah Umum dalam Menetapkan Sifat Allah
Setelahnya beliau mengatakan:
فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ وَعُدِّلَتْ رُوَاتُهُ، نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نَرُدُّهُ، وَلَا نَجْحَدُهُ، وَلَا نَتَأَوَّلُهُ بِتَأْوِيلٍ يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ
“Maka ini dan apa yang serupa dengannya, dari dalil-dalil yang shahih sanadnya dan adil para perawinya, kita beriman dengannya, tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, dan tidak mentakwilnya dengan takwil yang menyelisihi zahirnya.”
Artinya, beliau tidak menyebutkan di dalam kitab ini semua sifat-sifat Allah. Jika kita menemukan dalam Al-Qur’an atau hadis yang shahih sebuah sifat, maka sikap kita sama: kita harus mengimaninya.
Tidak boleh kita mentakwilnya, seperti mentakwil اسْتَوَىٰ (istiwa’) dengan اسْتَوْلَىٰ (istaula/menguasai), atau turunnya Allah ditakwil dengan turunnya malaikat. Seseorang tidaklah mentakwil kecuali karena dua kesalahan besar:
- Tasybih: Dia membayangkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, sehingga dia merasa harus mengubah maknanya.
- Ta’thil: Ketika dia meninggalkan makna yang shahih, dia jatuh ke dalam pengingkaran terhadap sifat Allah.
Adapun Ahlus Sunnah, mereka tidak perlu mentakwil karena sejak awal meyakini bahwa sifat Allah sesuai dengan keagungan-Nya dan tidak sama dengan sifat makhluk.
وَلَا نُشَبِّهُهُ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا بِسِمَاتِ الْمُحْدَثِينَ
“Dan kita tidak menyerupakan-Nya dengan sifat-sifat makhluk, tidak pula dengan ciri-ciri sesuatu yang baru (diciptakan).”
Kita menetapkan sebuah sifat tanpa berlebihan hingga menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman:
- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.”)
- فَلَا تَضْرِبُوا لِلهِ الْأَمْثَالَ (“Maka janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah.”)
- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (“Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”)
- هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (“Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?”)
وَنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ
“Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak ada yang serupa dengan-Nya dan tidak ada yang sebanding dengan-Nya.”
Setiap apa yang terbayang di dalam pikiran atau terbetik di dalam perasaan kita, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Itu adalah waswas dari setan, karena kita tidak pernah melihat Allah dan tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat-Nya.
Penetapan Sifat Istiwa’ dan ‘Uluww (Ketinggian)
Kemudian beliau mengatakan, di antara sifat yang harus kita tetapkan adalah sifat istiwa’ bagi Allah.
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ
“(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, yang ber-istiwa’ di atas ‘Arsy.” (QS. Thaha: 5)
Istiwa’ dalam bahasa Arab memiliki makna عَلَا وَارْتَفَعَ وَصَعَدَ وَاسْتَقَرَّ (meninggi, naik, berada di atas, dan menetap). Lafaz ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (kemudian Dia ber-istiwa’ di atas ‘Arsy) disebutkan enam kali dalam Al-Qur’an, yang semakin menegaskan sifat ini. Kewajiban kita adalah menetapkannya tanpa menyerupakan dengan istiwa’ makhluk dan tanpa mentakwilnya menjadi اسْتَوْلَىٰ (menguasai), karena takwil tersebut mengandung makna batil bahwa seakan-akan Allah sebelumnya tidak menguasai ‘Arsy.
Selanjutnya, beliau menyebutkan sifat Al-‘Uluww (ketinggian), yang berbeda dengan istiwa’.
- Istiwa’ adalah sifat fi’liyah (sifat perbuatan) yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ber-istiwa’ di atas ‘Arsy setelah menciptakan langit dan bumi.
- Al-‘Uluww adalah sifat dzatiyah (sifat Dzat) yang senantiasa ada pada Dzat Allah, baik sebelum maupun sesudah ber-istiwa’. Allah senantiasa Maha Tinggi.
Dalilnya adalah firman Allah:
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
“Apakah kamu merasa aman terhadap Dzat yang di atas langit?” (QS. Al-Mulk: 16)
Makna فِي السَّمَاءِ adalah عَلَى السَّمَاءِ (di atas langit) atau فِي الْعُلُوِّ (di ketinggian).
Kemudian beliau menyebutkan hadis tentang muamalah dengan budak wanita (jariah). Ketika seorang sahabat ingin membebaskan budak wanitanya, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengujinya terlebih dahulu:
- Nabi bertanya: أَيْنَ اللهُ؟ (Di manakah Allah?)
- Ia menjawab: فِي السَّمَاءِ (Di atas langit).
- Nabi bertanya: مَنْ أَنَا؟ (Siapakah aku?)
- Ia menjawab: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ (Engkau adalah Rasulullah).
Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
“Bebaskanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman.” (HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa keyakinan seorang mukmin adalah meyakini Allah berada di atas. Fitrah manusia pun mengakui hal ini.
Ucapan Imam Malik tentang Istiwa’
Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah ditanya tentang ayat الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. Seseorang bertanya, “كَيْفَ اسْتَوَىٰ؟” (Bagaimana cara Allah ber-istiwa’?).
Maka Imam Malik menunduk hingga wajahnya memerah, lalu menjawab dengan sebuah kaidah agung:
الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ
- Al-Istiwa’ ghairu majhul (Istiwa’ itu maknanya diketahui).
- Wal-kaifu ghairu ma’qul (Adapun tata caranya/kaifiatnya tidak dapat dijangkau oleh akal).
- Wal-imanu bihi wajibun (Beriman kepadanya adalah wajib).
- Was-su’alu ‘anhu bid’ah (Dan bertanya tentangnya (tentang “bagaimana”-nya) adalah bid’ah).
Setelah itu, beliau memerintahkan agar penanya tersebut dikeluarkan dari majelisnya. Kaidah ini berlaku untuk semua sifat Allah.
Tanya Jawab
1. Apakah boleh meminta dirukiah karena merasa tidak mampu melakukan rukiah mandiri?
Boleh, meminta untuk dirukiah bukanlah sesuatu yang haram. Namun, ada keutamaan yang lebih tinggi bagi orang yang tidak meminta untuk dirukiah, yaitu termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jika mampu, rukiah mandiri lebih utama. Jika ada orang lain yang menawarkan untuk merukiah tanpa kita minta, itu tidak mengurangi keutamaan tersebut.
2. Mohon penjelasan tentang perkataan Hasan al-Bashri bahwa cinta dunia adalah dosa besar yang paling besar.
Wallahu a’lam, mungkin yang dimaksud adalah cinta dunia yang berlebihan, yang mengalahkan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya, dan akhirat, sehingga membuatnya menghalalkan segala cara dan melupakan akhirat. Adapun cinta dunia yang wajar dan proporsional, seperti mencintai keluarga dan harta tanpa melebihi cinta kepada Allah, maka itu tidak tercela.
3. Bagaimana dengan orang yang qana’ah “kebablasan”, bekerja seadanya hingga istri dan anaknya terlantar?
Ini bukan qana’ah, tetapi kemalasan. Qana’ah adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan setelah berusaha secara maksimal. Seorang muslim dituntut untuk profesional dan bekerja keras. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ (“Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”). Ia harus berusaha maksimal, setelah itu barulah ia bersikap qana’ah terhadap hasil yang didapat.
4. Mohon nasihat bagi seorang istri yang berilmu dan ingin mengajarkan Al-Qur’an, tetapi suaminya tidak siap berbagi waktu dan perhatian istrinya.
Seorang istri wajib mentaati suaminya dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat). Mengajarkan Al-Qur’an hukumnya adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Jika suami belum mengizinkan, maka ketaatan kepada suami harus didahulukan karena itu adalah kewajiban ‘ain (individu) baginya. Hendaknya ia tidak berhenti berkomunikasi dengan baik kepada suaminya, sambil terus menunjukkan bahwa aktivitasnya tidak akan melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Mungkin dengan melihat dampak positifnya, hati suami akan luluh dan mendukungnya. Keseimbangan adalah kunci.